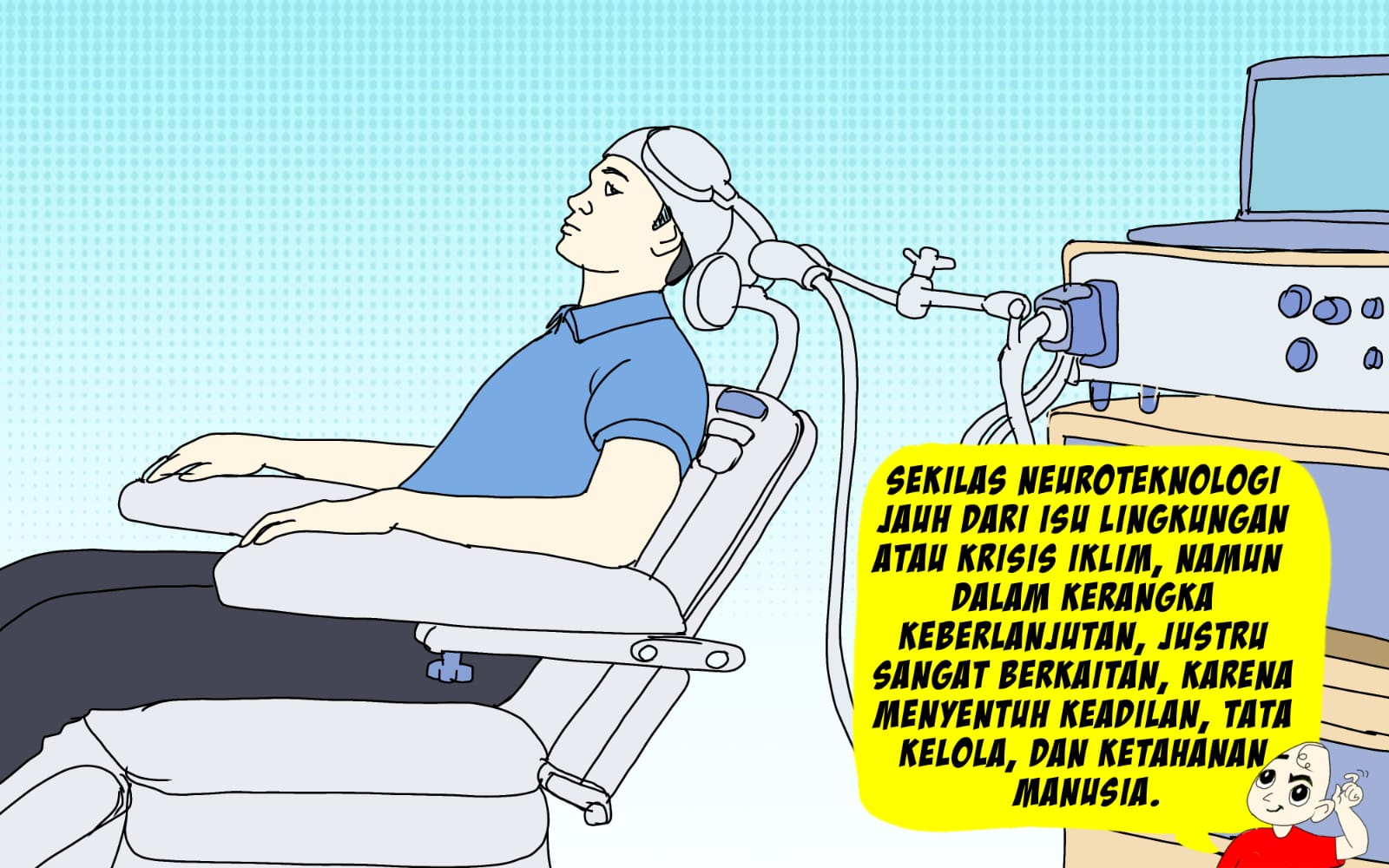Hari ini, 22 Juni, adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu ditandatanganinya Piagam Jakarta oleh Tim Sembilan perumus Dasar Negara yang diketuai oleh Bung Karno. Sebagai hari yang bersejarah, ada baiknya kita merenung, menggali hikmah dan makna dari peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini.
Meski sudah merupakan hasil kesepakatan Tim Sembilan, namun di luar sidang ternyata keputusan ini kembali memancing terjadinya perdebatan. Johannes Latuharhary, Samratulangi dan I.G. Ketoet Poedja mewakili aspirasi kelompok non-Muslim dan Indonesia Timur mengusulkan agar tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta yaitu “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan karena dianggap kurang mengakomodir pemeluk dan kepercayaan lain di luar Islam.
Usulan ini ditentang beberapa wakil kelompok Islam. Ki Bagoes Hadikusumo, Agus Salim, KH. Wahid Hasyim menginginkan agar tujuh kata tersebut tetap ada. Bahkan Bung Karno sendiri juga menginginkan agar Piagam Jakarta diterima tanpa ada perubahan. Menurut Bung Karno, Piagam Jakarta adalah rumusan terbaik yang dapat menghilangkan perselisihan antara golongan Islam dan nasionalis. Bung Karno khawatir penghapusan tujuh kata akan membuka perdebatan lagi antara kedua kelompok. “Jadi, manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini: jadi perselisihan terus nanti,” kata Sukarno mempertahankan Piagam Jakarta.
Untuk menengahi perdebatan tersebut, Wongsonagoro mengusulkan jalan tengah, yaitu agar kewajiban menjalankan hukum agama tidak hanya diwajibkan bagi umat Islam, sebagaimana tercermin dalam tujuh kata yanag ada di Piagam Jakarta, tapi juga seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia.
Pendapat ini ditentang oleh oleh Djajadiningrat dengan alasan hal tersebut akan menimbulkan fanatisme. “Apakah hal ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa shalat, dan lain-lain,” katanya.
Atas terjadinya perdebatan ini, Hatta mengusulkan agar tujuh kata tersebut diganti dengan “Yang Maha Esa” demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setelah melalui perdebatan dan lobi, akhirnya disepakati tujuh kata tersebut dihilangkan sehingga sila pertama yang menjadi Dasar Negara berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.
Dalam beberapa buku sejarah disebutkan terjadinya kompromi ini karena peran Kasman Singodimejo. Misalnya, Yudi Latif dalam salah satu bukunya menyebutkan Kasman Singodimedjo dan Teuku M Hasanlah yang membujuk Ki Bagus agar menerima saran Mohammad Hatta. Manurut Yudi Kasmanlah yang berhasil membujuk dan meyakinkan tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata piagam Jakarta.
Di sisi lain ada kisah yang tidak tercatat dalam sejarah namun berkembang dari mulut ke mulut di kalangan komunitas NU, yang menyebutkan penghilangan tujuh kata piagam Jakarta tidak lepas dari peran KH. Hasyim Asy’ari yang saat itu menjabat sebagai Rais Akbar NU dan Ketua Masyumi. Disebutkan, ketika muncul perdebatan mengenai penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, Soekarno memerintahkan KH. Wahid Hasyim bersama beberapa orang menghadap KH. Hasyim untuk meminta saran dan pendapat.
Dikisahkan oleh beberapa Kiai NU, di antaranya KH. Said Aqil Syiraj, KH. Muchid Muzadi, KH. Marzuki Mustamar, saat KH. Wahid Hasyim menjelaskan mengenai dasar negara hasil rumusan Tim Sembilan dan perdebatan mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakaarta, kemudian KH. Hasyim bertanya: “Apakah kalau tujuh kata dihilangkan umat Islam masih boleh menjalankan syariat Islam? Apakah kalau tujuh kata dihilangkan umat Islam masih boleh berdakwah di negeri ini?”
Atas pertanyaan yang disampaikan Kiai Hasyim ini, dengan tegas KH. Wahid menjawab bahwa meski tujuh kata rumusan Piagam Jakarta tersebut dihilangkan, umat Islam tetap diwajibkan menjalankan syariah Islam dan diperbolehkan melaksanakan dakwah Islam di Indonesia. Dengan kata lain, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tetap memberikan perlindungan pada umat Islam untuk menjalankan syariah dan melaksanakan dakwah, meskipun tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan
Setelah mendengar jawaban dari KH. Wahid, kemudian Kiai Hasyim menyampaikan sikapnya. "Wahid, saya setuju tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan, yang penting Indonesia kuat dulu, persatuan dan kesatuan kuat dulu. Di atas negara inilah kita berdakwah, kita berjuang mensyiarkan agama Islam, kita bangun masjid, pesentren, madrasah, dan majelis taklim," kata Kiai Hasyim sebagaimana dituturkan Said Aqil.
Terlepas dari siapa yang berperan dalam penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, satu hal yang penting dicatat adalah umat Islam Indonesia memiliki kearifan yang sangat tinggi dalam menerapkan ajaran agamanya di tengah keberagaman bangsa. Para kiai, ulama, habaib dan tokoh Islam memiliki jiwa besar, sehingga dapat bertenggang rasa dan menerima aspirasi saudara sebangsa tanpa mempertimbangkan kuantitas. Pemikiran dikotomik mayoritas-minoritas tidak tercermin dalam pemikiran pendirikan ara pendiri bangsa. Sebaliknya kepentingan kelompok benar-benar ditanggalkan dan diletakkan di atas kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara.
Tidak dapat dibayangkan kalau pada saat itu para pendiri bangsa yang menjadi pemimpin umat Islam berpikir sempit, simbolik dan tekstual, hampir dapat dipastikan perdebatan akan berlarut-larut dan berkepanjangan. Masing-masing pihak akan adu ayat dan dalil untuk memperkuat argumentasinya. Jika sudah demikian, bukan tidak mungkin konflik dan perpecahan akan terjadi, sehingga kemerdekaan bangsa yang menjadi hal yang lebih penting dan substansial menjadi terabaikan. Andaikan terjadi, kemerdekaan bangsa ini akan terancam perpecahan akibat fanatisme ideologis sebagaimana yang terjadi di India dan Pakistan.
Untunglah hal seperti ini tidak terjadi di negeri ini. Para pendiri bangsa dan pemimpin umat di negeri ini memiliki kearifan yang tinggi. Sikap arif dan bijak ini timbul karena mereka tidak berpikir simbolik tekstual, sebaliknya mereka berpikir substansial dan fungsional. Cara perpikir seperti inilah yang membuat mereka dapat membedakan antara simbol (yang dapat dikompromikan) dan substansi (yang harus dipertahankan), antara yang ushul/pokok (yang tidak dapat diubah) dan furu’ (yang dapat diubah).
Melalui pola pikir ini mereka dapat menerima Pancasila sebagai Dasar Negara dan NKRI sebagai bentuk negara. Bagi para ulama Nusantara, sekalipun NKRI bukan negara Islam dan dasar negaranya bukan Islam (Qur’an dan Hadits), namun NKRI yang berdasar Pancasila merupakan negara yang memberikan jaminan perlindungan bagi umat Islam menjalankan syariah.
Selain itu, meskipun Pancasila bukan agama, hanya hasil pemikiran manusia, tetapi Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dengan kata lain, Pancasila adalah hasil ijtihad ulama Nusantara agar nilai-nilai dan ajaran Islam dapat diamalkan di bumi Indonesia. Dengan pola pikir seperti inilah para ulama dan umat Islam Indnesia dapat menerima Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pola pikir seperti ini bukan semata-mata karena dorongan pemikiran sekuler, tanpa dasar pemahaman agama yang memadai. Sebaliknya pemikiran ini justru karena penguasaan perangkat ilmu agama yang sangat dalam dan luas. Para ulama Nusantara yang menjadi pendiri bangsa adalah orang-orang alim yang menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, tafsir, balaghah, mantiq, tata bahasa (nahqu shorof), tasassuw dan sejenisnya. Pendeknya penerimaan NKRI sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai dasar negara dengan penghilangan tujuh kata dari Piagam Jakarta merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan pada kaidah keilmuan yang sesuai syariat Islam.
Atas dasar inilah maka tidak selayaknya memperdebatkan hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tanpa keilmuan agama yang memadai, apalagi cuma berdasarkan sentimen, fanatisme dan kepentingan politik praktis. Dari pada sibuk berdebat sambil menghidukan semangat fanatisme buta, akan lebih baik memperjuangkan penerapan Pancasila secara maksimal dengan meniru kearifan para ulama pendiri bangsa.