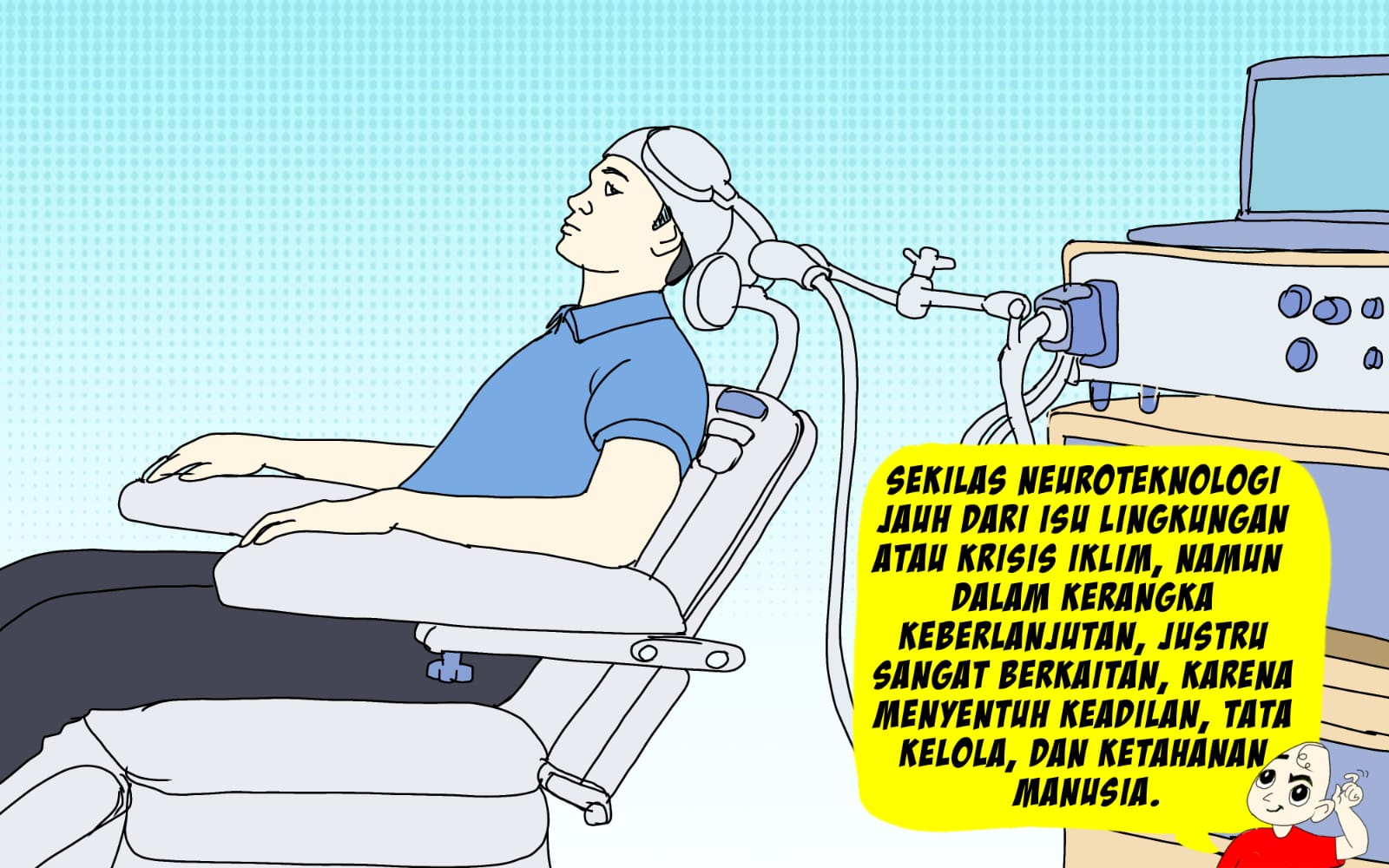Ada kisah menarik yang terjadi di kalangan Kiai NU terkait dengan etika dalam politik praktis, yaitu kisah Kiai Bisri Syansuri dan Mbah Wahab Chasbullah. Kisah ini dapat dijadikan cermin dan sumber inspirasi dalam menyikapi situasi politik saat ini yang penuh ketegangan dan cenderung mengabaikan etika.
Dikisahkan, pasca ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berdampak pada pembubaran Konstituante dan pembentukan DPR-GR, NU ditawari masuk menjadi anggota DPR-GR oleh Bung Karno. Tawaran ini menimbulkan perbedaan pendapat, di kalangan ulama NU.
Sebagian ulama NU yang dimotori oleh KH Bisri Syansuri menolak tawaran tersebut dengan alasan: tindakan Bung Karno membubarkan Konstituante dan membentuk DPR-GR adalah bentuk penggunaan kekuasaan rakyat secara tidak sah, atau dalam istilah fiqh disebut ghasab. Karena, menurut Kiai Bisri, kekuasaan rakyat itu berada di tangan Konstituante yang merupakan hasil dari pemilu. Kalau NU masuk menjadi anggota DPR-GR bentukan Bung Karno, maka itu artinya NU mengakui dan mengesahkan ghasab kekuasaan yang dilakukan oleh Bung Karno.
Pendapat Kiai Bisri ini ditolak oleh sekelompok kiai lain yang dimotori oleh Mbah Wahab Chasbullah. Menurut Mbah Wahab, NU justru harus menerima tawaran Bung Karno masuk menjadi anggota DPR-GR. Mbah Wahab juga menggunakan kaidah fiqh sebagai dasar argumentasinya, yaitu “ma lam yudraku kulluhu la yutraku kulluh” (sesuaatu yang tidak dapat dicapai secara keseleuruhan tidak boleh ditinggalkan semua). Artinya, tidak boleh meninggalkan suatu kesempatan secara total hanya karena tidak dapat dicapai secara keseluruhan. Sekecil apapun kesempatan harus diambil dan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
“Kalau NU menolak masuk DPR-GR, lalu lewat saluran apa aspirasi NU dan umat Islam dapat disampaikan?” demikian kata Mbah Wahab. Apa lagi pada saat itu Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, sehingga tidak memiliki hak untuk masuk di DPR. Menurut Mbah Wahab, masuknya NU menjadi anggota DPR-GR itu merupakan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan kepentingan umat di forum resmi negara. Melalui penggunaan kaidah memanfaatkan yang minimal ini, maka masuknya NU menjadi anggota DPR-GR bukan untuk melegitimasi ghasab kekuasaan yang dilakukan oleh Bung Karno, sebagaimana logika yang dibangun Mbah Bisri, sebaliknya justru memanfaat kesempatan minimal yang ada untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat.
Perbedaan pemikiran ini cukup frontal dan tajam, dan berlangsung secara terbuka di publik. Namun benturan ini hanya sebatas pemikiran. Secara pribadi mereka tetap berhubungan secara baik dan akrab. Tidak ada caci maki, saling merendahkan, dan persekusi antara keduanya. Bahkan, keduanya tidak memprovokasi umat untuk mendukung pikiran masing-masing. Sikap inilah yang mebuat rakyat tetap tenang, tidak terbelah, tidak terjebak dalam perpecahan, meskipun di antara mereka ada yang mendukung Kiai Bisri maupun Mbah Wahab.
Yang menarik, ketika NU memutuskan masuk menjadi anggota DPR-GR, Kiai Bisri menerima keputusan tersebut secara legowo. Beliau tidak menganggap keputusan tersebut sebagai kesalahan, karena tidak sesuai dengan pemikirannya. Meskipun beliau menerima keputusan tersebut, namun menolak untuk dijadikan anggota DPR-GR. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pemikirannya sendiri.
“Saya menerima secara ikhlas keputusan NU masuk menjadi anggota DDPR-GR, dan saya akan mendukungnya. Tapi tolong jangan pilih saya menjadi angggota DPR-GR, karena saya harus menghormati gagasan saya sendiri,” demikian kata Mbah Bisri yang diceritakan Gus Dur kepada penulis.
Contoh lain yang dapat dijadikan teladan dalam berpolitik adalah sikap para anggota BPUPK dalam perdebatan merumuskan bentuk dan dasar negara. Saat itu terjadi perdebatan yang sangat tajam antara kubu nasionalis sekuler dengan kelompok religius formal. Perdebatan itu begitu tajam di ruang sidang, namun di luar sidang mereka tetap bersahabat secara akrab, saling peduli dan membantu menyelesaikan persoalan pribadi yang dihadapi masing-masing anggota.
Misalnya kisah tetang I.J. Kasimo, seorang politisi Katolik yang menginisiasi penggalangan dana untuk membelikan rumah Prawoto, koleganya dari Masyumi yang tidak memiliki rumah. Sebagai seorang politisi yang jujur dan bersih, Prawoto menolak berbagai tawaran dari para pengusaha, padahal seluruh pikiran dan tenaganya dicurahan untuk negara. Melihat kondisi Prawoto yang tidak memiliki rumah, I.J. Kasimo berinisiatif menggalang dana dari para politisi lintas partai. Dana yang terkumpul tersebut kemudian diserahkan kepada Prawoto untuk membeli rumah di Jalan Kertosono No. 4 Jakarta.
Yang menarik, perdebatan itu tetap terjadi pada wilayah pemikiran dan konsep. Tidak ada yang menyerang individu dan mendeskriditkan kelompok hanya karena perbedaan pendapat. Tidak ada yang menuduh sesat, kafir, apalagi sampai menghalalkan darah lawan bicara. Mereka tidak hanya berdebat adu argumentasi, tetapi mereka juga memiliki kearifan untuk titik temu yang dapat dijadikan pijakan bersama dalam perbedaan. Sehingga perdebatan dan perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi khazanah pemikiran yang memperluas dan memperkaya perspektif kebangsaan.
Mengapa para pendiri bangsa dapat menjaga moral etik dalam pertarungan politik dan perbedaan pemikiran yang tajam?
Pertama, karena para pendiri bangsa yang terjun dalam politik praktis pada saat itu adalah orang-orang berkarakter, yang tidak semata-mata menjadikan politik sebagai alat perebutan kekuasaan. Dengan kata lain, yang mereka perjuangkan dalam politik adalah nilai-niai luhur, bukan semata-mata meraih kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Visi seperti ini tercermin dalam sikap Mbah Bisri yang menolak menjadi anggota DPR-GR demi menjaga konsistensi pemikirannya. Selain itu, Mbah Bisri juga ingin memberikan penghormatan kepada orang yang berseberangan dengan pemikirannya untuk menduduki jabatan di DPR-GR.
Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kubu Mbah Wahab yang memberikan kesempatan kepada Mbah Bisri untuk menduduki jabatan di DPR-GR. Sebagai “pemenang” kubu Mmbah Wahab tidak jumawa, menyingkirkan kubu lawan. Inilah contoh politik yang berahlak, yang kalah mengormati pemenang dan yang menang memuliakan yang kalah. Dengan demikian politik menjadi bermartabat.
Kedua, para pendiri bangsa menempatkan kepentingan yang lebih luas sebagai pijakan bersama. Dengan kata lain pijakan politik praktis mereka adalah kepentingan bangsa dan negara yang luas dan dalam, bukan kepentingan golongan dan individu yang sempit dan dangkal. Karena alas pergerakan politik praktisnya luas dan dalam, maka mereka tidak mudah retak dan pecah.
Ini sangat berbeda dengan politik yang berdasar pada kentingan pragmatis individu dan kelompok. Politik seperti ini akan mudah retak dan pecah. Kepentingan yang sempit dan dangkal akan membuat politisi terjebak dalam sikap pragmatis yang menghalalkan cara-cara kotor dan keji untuk merebut kekuasaan dan memenangkan pertarungan.
Mereka mengabaikan etika dan moral dalam berkompetisi. Mudah terjebak dalam klik, intrik dan saling sandera untuk mengamankan kepentingan masing-masing yang sempit dan dangkal. Karena, alas politik yag dijadikan pijakan bukan pada nilai dan kepentingan bangsa yang luas dan dalam, maka mereka mudah pecah, gampang terjebak pada perdebatan yang panjang dan melelahkan. Masing-masing ingin memperjuangkan kepentingan sendiri. Kalau saja terjadi kesepakatan, maka akan sangat mudah diingkari atau diubah karena kepentingan yang sempit tersebut.
Sikap dan perilaku politik para pendiri bangsa, sebenarnya dapat menjadi standar dan alat ukur untuk melihat karakter dan komitmen para politisi saat ini. Sekalipun omongan mereka sangat bijak, dan sikap mereka sangat santun, tapi kalau laku hidupnya tidak konsisten dengan apa yang diucapkan, menggunakan segala cara untuk mencapai kekuasaan, maka sebenarnya mereka bukanlah orang yang berkarakter. Artinya, mereka tetap saja sosok kerdil yang tidak berkarakter.
Demikian juga kalau ada politisi yang bicara berbusa-busa demi bangsa dan negara, tetapi berdebat keras dan bertele-tele di parlemen hingga menghabiskan waktu. Hanya membahas urusan sepele dan prosedural dengan mengabaikan kepentingan negara yang lebih substansial. Maka, akan sulit menyatakan bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan negara, malah sebaliknya justru memperlihatkan adanya pertarungan kepentingan kelompok yang tajam.
Pendeknya, standar etik politisi adalah kepentingan bangsa dan negara yang termanifestasikan dalam kepentingan publik. Dan standar itu sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa baik secara tektual (konstitusi) maupun kontekstual(laku hidup yang dapat menjadi teladan).