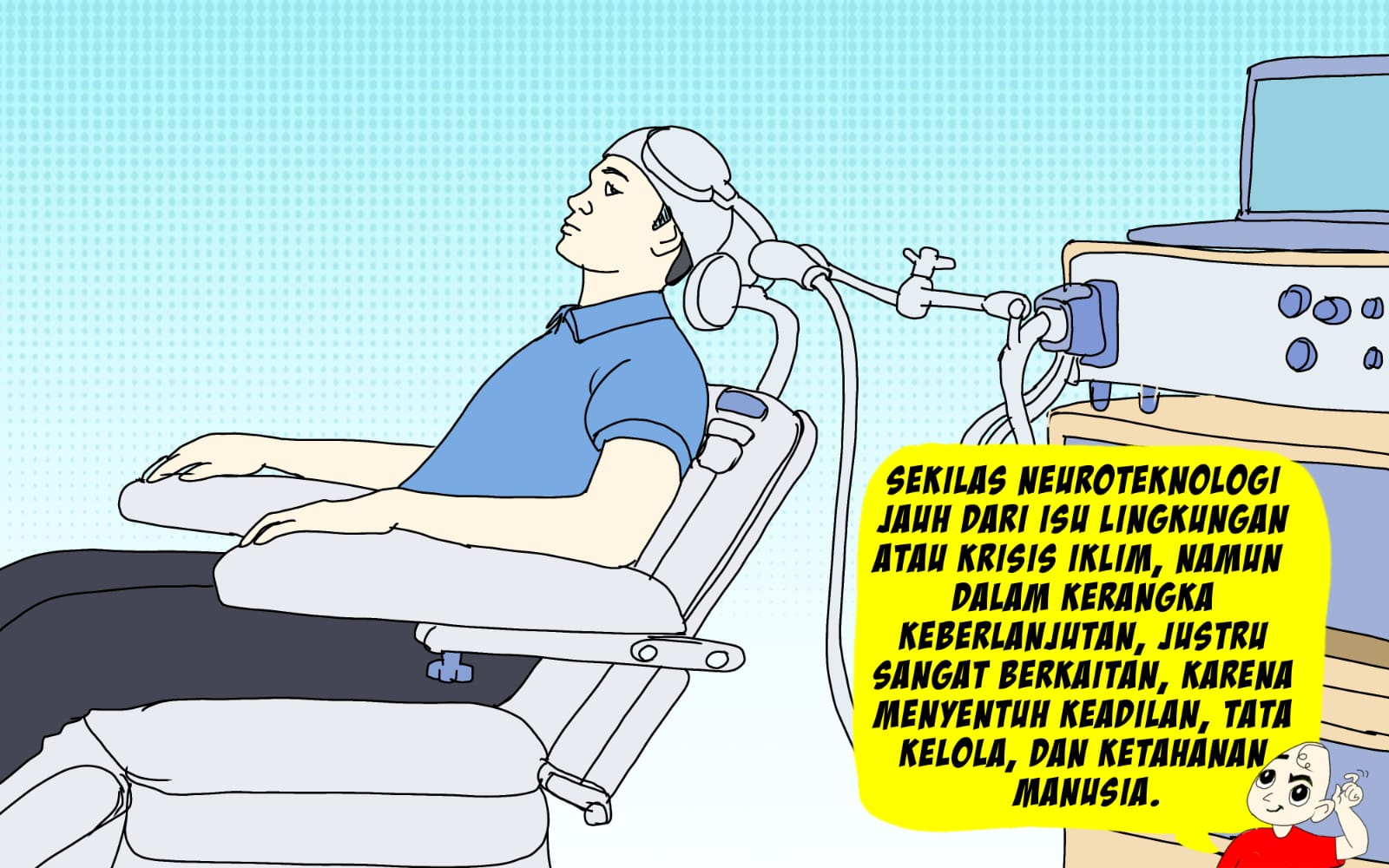Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, saya menemukan koperasi yang baru membeli 100 hektar hutan tropis asli untuk dilestarikan. Itu enklave yang jarang, di tengah kepungan agresi perkebunan sawit monokultur.
Koperasi? Di tengah hutan Kalimantan? Melestarikan alam?
Gabungan antara kearifan tradisional masyarakat adat, tata nilai lokal dan prinsip koperasi (gotong royong) dinilai merupakan rumus tepat untuk mencapai keadilan sosial dan ekologis, yang dalam beberapa dasawarsa terakhir merupakan isu global paling mendesak. Ini ditegaskan oleh Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi pada 2009.
Lewat kajian luas terhadap ratusan komunitas lokal dan masyarakat adat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, Ostrom menentang konsep usang "the tragedy of the common" tentang dilema pengelolaan sumber daya alam dan solusinya.
"The Tragedy of the commons" adalah judul sebuah esai yang ditulis oleh Garrett Hardin, seorang biolog, pada 1968.
Hardin beranggapan bahwa manusia pada dasarnya egois. Jika masing-masing manusia dibiarkan memanfaatkan "barang publik" (the commons), maka barang itu akan segera habis (depleted), tak menyisakan untuk semua orang.
Di situlah tragedinya: jika suatu barang dianggap publik, dan semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama, maka akhirnya tidak akan ada manfaatnya buat semua orang. Bagi Hardin, itu bukan hanya tragedi, tapi juga menunjukkan irasionalitas konsep "barang publik".
Hardin memberi contoh: jika setiap orang secara bersama boleh memanfaatkan padang rumput gembala kambing yang tidak dimiliki siapapun, maka tiap orang kuatir kambing orang lain akan lebih banyak makan rumput dan menghabiskannya. Itu akan memicu perlombaan yang akhirnya membuat padang rumput lebih cepat habis dan semua penggambala dirugikan.
Contoh lain adalah fenomena "overfishing". Perlombaan menangkap ikan di teluk atau laut yang dianggap milik bersama akan mengurangi jumlah ikan secara dramatis yang mempercepat kepunahannya. Atau ketika orang berlomba membuat sumur bor yang makin dalam untuk menyedot air tanah, yang memicu kelangkaan air bagi semua orang.
Pandangan Hardin tadi melukiskan dilema palsu yang dihadapi dalam pengelolaan hutan, lahan pertanian, sungai, teluk, dan laut. "Tragedy of the commons" memicu perlombaan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan yang akan merusak alam dan lingkungan hidup dengan konsekuensi yang panjang, termasuk perubahan iklim yang dihadapi manusia sekarang.
Solusi mencegah tragedi itu, menurut Hardin, adalah menghilangkan "barang publik" dengan menerapkan sebuah sistem aturan yang membatasi pemanfaatan dan memastikan kelestariannya.
Hardin menyarankan agar barang publik dikuasai oleh negara, yang bisa menegakkan aturan untuk membatasi hasrat individu. Atau membuat barang publik tadi menjadi barang privat, yang dikuasai entitas swasta, sehingga meminimalkan pemanfaatannya.
Solusi Hardin tadi memicu dua pandangan ekstrim dalam mazhab politik-ekonomi kontemporer: etatisme (kontrol penuh negara) versus liberalisme (privatisasi).
Elinor Ostrom punya pandangan berbeda. Bagi Ostrom, baik negara maupun pasar bukanlah pengelola dan penjaga terbaik sumber daya alam. Rakyat lah, di tingkat komunitas, yang bisa melakukannya dengan lebih baik.
Studi Ostrom menunjukkan interaksi manusia dan ekosistem telah terjadi selama berabad-abad dan memperlihatkan bahwa pemanfaatan sumber daya oleh sekelompok orang (komunitas adat, koperasi) bisa rasional dan bisa mencegah habisnya sumber daya alam tanpa intervensi negara atau tanpa mekanisme pasar kapitalistik.
Masyarakat-masyarakat adat lokal, menurut Ostrom, bisa mengelola sungai, hutan dan gunung secara bersama, dengan cara merumuskan aturan bersama dari waktu ke waktu yang kemudian dilembagakan dalam hukum adat.
Beberapa masyarakat tradisional Indonesia seperti Baduy atau Dayak, misalnya, mengenal konsep hutan larangan dan sasi.
Mereka melarang melarang warga menebang pohon di lokasi dan waktu tertentu, atau melarang warga mengambil ikan di sungai dan teluk pada waktu-waktu tertentu. Itu memberi kesempatan bagi alam untuk memulihkan dirinya sendiri, sebuah model pengelolaan sumber daya alam secara lestari yang diilhami oleh adat setempat.
Di seluruh dunia, masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal memiliki koneksi kuat dengan alam, khususnya hutan. Secara total mereka diperkirakan mengelola lebih dari seperempat luas lahan dunia. Lahan itu berisi sekitar 80% keragaman hayati (flora dan fauna) seluruh planet dan berisi hutan penyerap karbon cukup signifikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Bahkan meski memiliki akses keuangan dan dukungan legal yang terbatas, mereka telah membuktikan diri sebagai penjaga kelestarian terbaik hutan dunia dan manfaat ekosistem tak ternilai seperti perannya sebagai penjamin ketersediaan air bersih.
Mereka menyumbang konservasi alam lebih baik dari kawasan-kawasan lindung yang ditetap pemerintah. Sebuah tudi yang dilakukan pada 2000-2012 di Amazon menunjukkan bahwa laju penggundulan hutan yang dikelola masyarakat adat 2 atau 3 kali lebih rendah dari kawasan di luarnya.
Di Indonesia sendiri ada lebih dari 2.400 masyarakat adat, berisi 17 juta orang, yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat.
Pada 2015, organisasi itu mendapat Elinor Ostrom Award karena dinilai berjasa memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat yang belakangan ini cenderung dipinggirkan atas nama modernisme dan globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, AMAN juga memperjuangkan legislasi UU Masyarakat Adat, meski belum berhasil.
Menurut Alexandre Guttmann dari Universitas Sorbone, Prancis, nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat adat dan prinsip koperasi mendorong penguatan paham baru dalam kajian pembangunan: social and solidarity economy (SSE), yang mengatasi ketimpangan antara ekonomi pasar kapitalis dan regulasi top-down oleh negara. Keduanya merupakan rumus tindakan kolektif untuk memecahkan masalah keadilan sosial dan kerusakan alam.