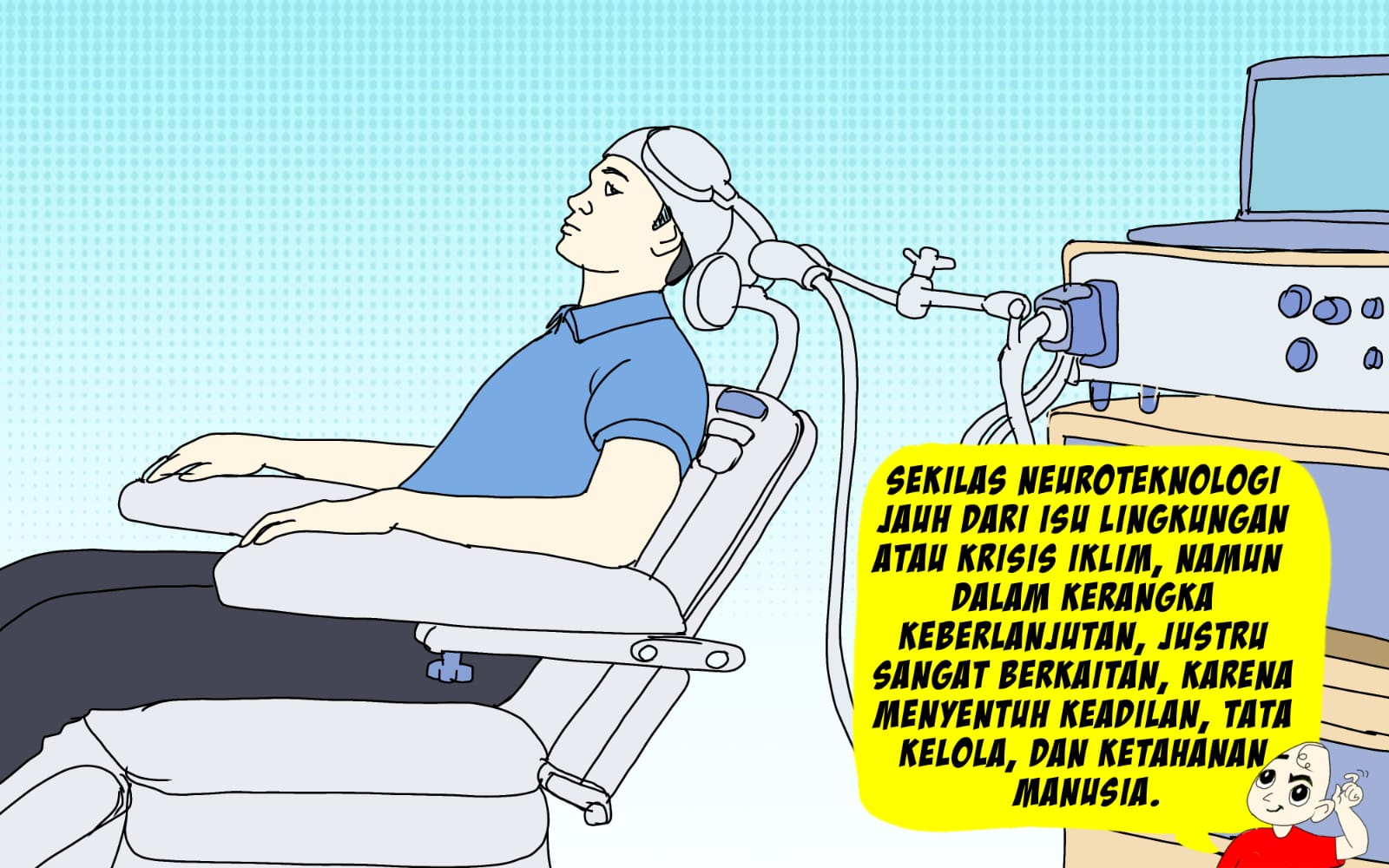Ada fenomena menarik dalam realitas politik Indonesia saat ini, yaitu tingginya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran (PG) dibanding pasangan Anies-Muhaimin (AM) dan Ganjar-Mahfud (GM) sebagaimana terlihat pada laporan terakhir beberapa lembaga survei yang kredibel.
Beberapa data tersebut di antaranya, LSI menunjukkan PG 43,3%; AM 25,3% dan GM 22,9%, Polling Institute yang merilis hasil surveinya pada 27 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PG mencapai 46,1%, sedangkan AM di angka 24,3% dan GM pada angka 24,1%. Elektabilitas PG mengalami kenaikan dibanding bulan November sebesar 43,2%. Hasil survei CSIS menempatkan PG di posisi pertama dengan nilai elektabilitas 43,7%, sedangkan AM dan GM masing-masing berada pada angka 26,1% dan 19,4%. Hasil survei CSIS dirilis pada 27 Desember 2023.
Lembaga survei lainnya yang menempatkan pasangan PG pada posisi tertinggi adalah Indikator Politik Indonesia (46,7%); Indikator Publik Nasional (50,2%), Litbang Kompas (39,3), Arus Survei Indonesia yang melakukan elektabilitas pasangan Capres-cawapres di pulau Jawa menunjukkan PG unggul dengan angka 34,2%; Populi Center (46,7%); Poltracking Indonesia (45,2), naik 5% dibanding bulan sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia (46,7%).
Data-data ini menarik, karena selama ini terjadi kampanye negatif yang sangat masif terhadap pasangan PG. Beberapa isu kampanye negatif yang marak di medsos adalah soal pelanggaran etika, politik dinasti, Capres Bocil, merusak demokrasi, menghancurkan bangsa dan beberapa tudingan negatif lainnya yang dialamatkan pada Jokowi dengan tujuan merusak citra pasangan PG. Pendeknya, hampir tak ada cintra positif yang dialamatkan pada Jokowi dan pasangan PG. Mereka seolah menjadi tempat sampah untuk menuangkan segala macam tuduhan, caci maki dan sumpah serapah.
Tidak hanya itu, untuk menurunkan citra pasangan PG, juga muncul isu keberpihakan aparatur negara, intimidasi, kecurangan yang mengekspos beberapa kasus yang dianggap menguntungkan pasangan calon (Paslon) PG. Di antaranya kasus kekerasan oknum TNI di Boyolali, pernyataan dukungan Satpol PP di Garut, penurunan Baliho Paslon tertentu di beberapa daerah dan beberapa kasus lain. Tapi kampanye negatif itu ternyata tidak dapat menurunkan hasil survei elektabilitas PG.
Mengapa hal ini dapat terjadi? Padahal seluruh kampanye negatif tersebut didukung dengan fakta dan data yang valid dan akurat, didasari pada basis argumen dan nilai etik yang yangat kuat. Mengapa teriakan kaum intelektual, akademisi dan aktivis yang memenuhi ruang publik ini seolah tidak dapat menggerakkan masyarakat atau mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menolak pasangan yang dianggap cacat moral dan etik.
Menurut penulis, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjanagan imajinasi politik antara kelas menengah terdidik dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Politik yang diimajinasikan oleh para aktivis, intelektual dan pengamat berbeda dengan yang ada dalam imajinasi masyarakat pemilih secara mayoritas. Bagi masyarakat awam isu tentang demokrasi, pelanggaran konstitusi, etika politik, dinasti, kekerasan aparat, kecurangan pemilu dan sejenisnya, kurang menarik karena tidak ada dalam imajinasi mereka.
Kesenjangan imajinasi politik ini berdampak pada perbedaan dalam melihat dan menentukan prioritas politik. Bagi para aktivis, intelektual dan pengamat, isu-isu yang mereka munculkan saat ini merupakan sesuatu yang urgent dan menjadi agenda utama politik nasional yang harus menjadi perhatian dalam pemilu. Tapi bagi masyarakat awam isu-isu seperti itu dianggap bukan sesuatu yang penting, bukan prioritas yang harus direspon serius. Mengatasi knalpot bronk yang membuat bising telinga tapi tidak ada yang berani menindak mungkin lebih menarik dan menjadi prioritas bagi mereka. Sehingga mereka kurang tertarik mempermasalahkan tindakan kekerasan oknum TNI. Bahkan tindakan yang menurut para aktivis dan kaum intelektual membahayakan demokrasi, melanggar hukum dan mengancam kedaulataan rakyat itu justru merupakan tindakan heroik terhadap mereka yang ugal-ugalan dan meresahkan.
Fenomena ini mestinya menjadi refleksi para akademisi, aktivis dan pengamat politik di negeri ini. Realitas sosiologis kultural masyarakat Indonesia tidak semuanya berada pada tahap rasional-modern. Secara sosiologis masih banyak di antara kita, warga bangsa Inddonesia, yang berada pada tahapan fethis (primitif) dan metafisik. Pada masyarakat seperti ini, imajinasi politik masih terbatas pada sistem nilai yang ada dalam tradisi dan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan praktik kehidupan mereka. Idealitas politik yang diimajinasikan kaum intelektual dan para pengamat belum sepenuhnya tertangkap oleh mereka. Seandainya mereka bisa memahami belum tentu dapat mempraktikkan secara tepat karena adanya sistem nilai tradisional yang melingkupinya.
Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada adagium Jawa yang sarat nilai, yaitu “bener durung mesti pener." Adagium ini mengandung pengertian suatu kebenaran itu belum tentu tepat dan sesuai. Artinya kebenaran itu harus tepat dan sesuai agar dapat diterima dan dijalankan. Suatu kebenaran yang disampaikan dan diterapkan dengan cara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kondisi sosial-budaya yang melingkupinya, maka kebenaran tersebut akan sulit diterima dan diterapkan.
Demokrasi, kebebasan memilih, melawan intimidasi, menolak otoritarianisme, melawan kecurangan pemilu, menegakkan konstitusi, menolak dinasti dan sejenisnya adalah suatu kebenaran. Tapi jika kebenaran itu disampaikaan dengan cara-cara yang tidak tepat (tidak pener), misalnya dengan caci maki, nyinyir, eksesif, berlebihan maka akan menimbulkan arus balik yang berujung penolakan. Dalam istilah Jawa disebut “bener ning ora pener,” benar tapi tidak tepat. Kesenjangan imajinasi inilah yang membuat sesuatu yang “bener” menjadi tidak “pener”. Ini artinya bersikap dan bertindak “bener tur pener” merupakan agenda besar para aktivis demokrasi, intelektual dan akademisi Indonesia.
Selain mengindikasikan adanya kesenjangan imajinasi politik, fenomena naiknya elektabilitas PG juga mencerminkan adanya sikap politik “romantik-melankolis” yaitu suatu preferensi politik yang lebih diarahkan oleh rasa iba, kasihan dan perasaan melankolis lainya. Seseorang yang tekesan dianiaya, dicecer, selalu dijelek-jelekkan, dipojokkan secara berlebihan justru menarik simpati dan empati masyarakat.
Realitas ini mestinya dipahami oleh tim kampanye dan pendukung paslon. Cara-cara kampanye yang memojokkan lawan, membuat tudingan negatif secara berlebihan, menyerang pihak lain secara arogan, ternyata dapat menimbulkan arus balik yang justru meningkatkan elektabilitas pihak yang diserang, meskipun serangan tersebut didukung dengan data yang valid dan nilai-nilai kebenaran yang kuat. Perlu ada cara-cara yang lebih kreatif dan simpatik untuk menarik perhatian konstituen.
Kita tidak dapat menyalahkan realitas sosiologis kultural masyarakat Indonesia yanag seperti ini. Sebaliknya hal ini justru menjadi tantangan bagi para akademisi, aktivis demokrasi dan para agen perubahan di negeri ini. Mereka perlu memahami dan mensikapi secara bijak realitas politik seperti ini. Dengan cara ini akan ditemukan batas-batas maksimal melakukan tekanan, kriitik dan cara-cara penyampaiannya. Tidak mudah bersikap: bener tur pener di tengah kepungan arus peradaban dan pertarungan kepentingan politik. Tapi di sinilah justru tantangan dan ujian utama dalam kerja kebudayaan membangun demokrasi yang sehat.